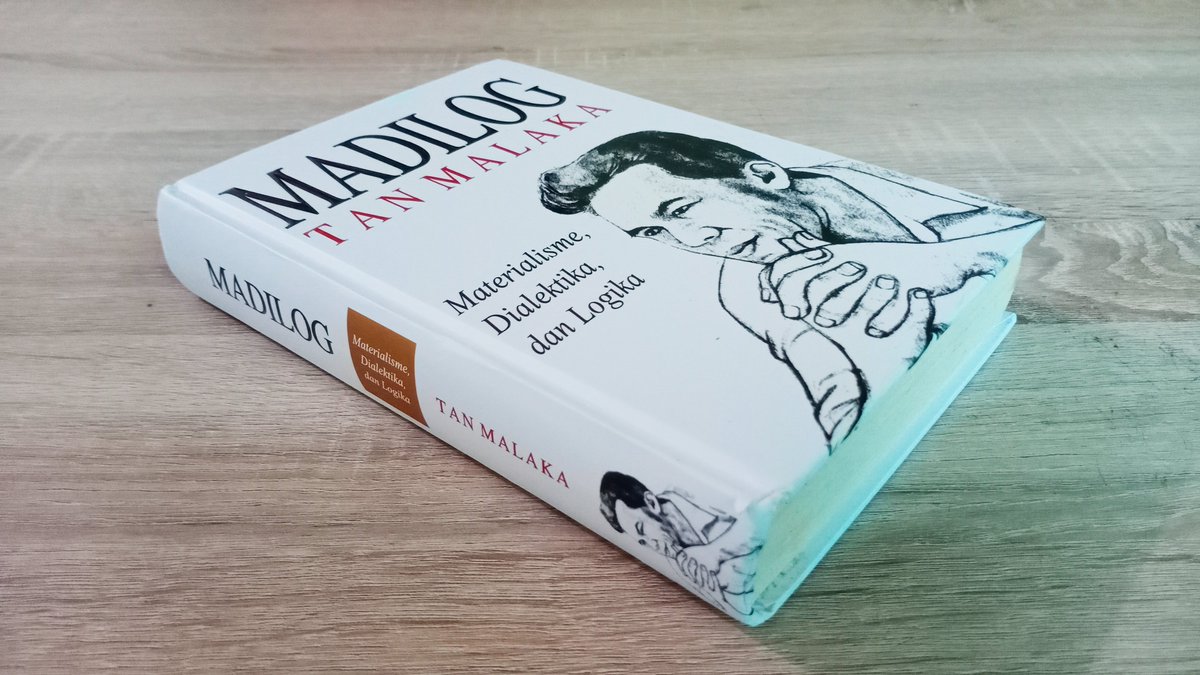Oleh: Sabaruddin Hasan – Jurnalis

OPINI, PilarSultra.com — Nama Tan Malaka dan konsep MADILOG (Materialisme, Dialektika, Logika) kerap diposisikan berhadap-hadapan dengan religiusitas. Di ruang publik, MADILOG sering dicurigai sebagai anti-agama, sementara religiusitas dianggap bertentangan dengan nalar kritis. Namun, pertentangan ini sejatinya lebih banyak lahir dari salah paham, bukan dari substansi pemikiran.
MADILOG lahir dari kegelisahan Tan Malaka terhadap cara berpikir masyarakat yang terjebak pada mistik, dogma, dan kepatuhan tanpa nalar. Ia tidak sedang memerangi Tuhan, melainkan cara berpikir yang mematikan akal sehat. Materialisme dalam MADILOG bukan ajakan untuk menuhankan benda, melainkan dorongan agar manusia berpijak pada realitas nyata, bukan ilusi. Dialektika bukan penolakan iman, melainkan pengakuan bahwa kehidupan bergerak melalui konflik dan perubahan. Sementara logika adalah alat agar manusia tidak mudah dibohongi—oleh kekuasaan, mitos, maupun simbol-simbol kosong.
Masalah muncul ketika religiusitas direduksi menjadi ritual tanpa refleksi. Di titik ini, agama tidak lagi membebaskan, tetapi justru membelenggu. Dogma diterima tanpa pertanyaan, kritik dianggap dosa, dan ketidakadilan ditoleransi atas nama takdir. Dalam kondisi seperti inilah, MADILOG terasa “berseberangan” dengan religiusitas—padahal yang ditentangnya bukan iman, melainkan kemalasan berpikir.
Sebaliknya, religiusitas yang matang sejatinya tidak alergi terhadap nalar. Banyak nilai agama justru sejalan dengan semangat MADILOG: kejujuran, keadilan, tanggung jawab sosial, dan keberpihakan pada yang lemah. Agama mengajarkan tujuan moral, sementara MADILOG menyediakan alat berpikir untuk memastikan tujuan itu diwujudkan secara rasional dan adil dalam kehidupan sosial.
Konflik antara MADILOG dan religiusitas menjadi tajam ketika agama diperalat sebagai alat legitimasi kekuasaan. Saat kemiskinan dianggap takdir, ketimpangan disebut ujian iman, dan kritik dilabeli pembangkangan, di situlah MADILOG hadir sebagai gangguan yang tidak diinginkan. Ia mengajukan pertanyaan sederhana namun berbahaya bagi status quo: siapa diuntungkan dari kondisi ini?
Maka, pertentangan antara MADILOG dan religiusitas sesungguhnya adalah pertentangan antara iman yang hidup dan iman yang beku. MADILOG tidak meniadakan Tuhan, tetapi menolak manusia berhenti berpikir atas nama Tuhan. Di tangan masyarakat yang dewasa, keduanya justru bisa saling menguatkan: agama memberi arah nilai, MADILOG menjaga agar arah itu tidak diselewengkan oleh kepentingan duniawi.
Dalam konteks Indonesia hari ini—di tengah banjir hoaks, politik identitas, dan simbolisme religius—pertemuan antara religiusitas yang reflektif dan MADILOG yang kritis menjadi kebutuhan mendesak. Bukan untuk saling menyingkirkan, melainkan untuk memastikan bahwa iman tetap membumi, dan nalar tetap bermoral.
Ketika Takdir Dijadikan Alibi Kemalasan
Ayat “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri” (QS. Ar-Ra’d: 11) adalah salah satu ayat paling revolusioner dalam sejarah pemikiran manusia. Ayat ini membongkar satu kebohongan besar yang sering bersembunyi di balik kata “takdir”: bahwa kegagalan adalah kehendak Tuhan, sementara usaha manusia tidak relevan.
Padahal, ayat ini justru menegaskan sebaliknya: Tuhan bekerja melalui sistem. Takdir bukan peristiwa acak, melainkan hukum sebab-akibat yang diciptakan Allah sendiri. Siapa yang belajar, bekerja, dan berdisiplin, besar kemungkinan berhasil. Siapa yang malas, menghindari ilmu, dan menolak perubahan, hampir pasti tertinggal. Ini bukan filsafat Barat—ini teologi Islam yang rasional.
Di titik inilah MADILOG Tan Malaka menjadi relevan dan sekaligus mengganggu. MADILOG memaksa manusia membaca realitas apa adanya. Ia menolak mistifikasi kegagalan. Ia bertanya: jika seseorang miskin, apakah benar semata-mata karena takdir, atau karena sistem ekonomi, pendidikan, dan kekuasaan yang timpang? Pertanyaan semacam ini sering dianggap “kurang iman”, padahal justru lebih jujur secara intelektual.
Masalah muncul ketika religiusitas direduksi menjadi kepasrahan pasif. Takdir dijadikan tameng untuk tidak berpikir, tidak melawan ketidakadilan, dan tidak memperbaiki sistem. Orang miskin disuruh bersabar, sementara sistem yang memiskinkan dibiarkan. Ini bukan iman—ini penjinakan kesadaran.
Namun, perlu diluruskan satu hal penting agar tidak tergelincir: kerja keras tidak otomatis berbanding lurus dengan kesuksesan individual. Di sinilah pemahaman “takdir sebagai sistem” harus lebih dalam. Jika ada orang rajin bekerja dan belajar tetapi belum sukses, itu bukan pembatalan hukum Tuhan, melainkan indikasi bahwa ada variabel sistemik lain yang tidak terlihat: akses, struktur ekonomi, ketimpangan modal, jaringan kekuasaan, bahkan ketidakadilan kebijakan.
Dengan kata lain, kegagalan bukan selalu kesalahan individu, tapi sering kali cacat sistem. Dan sistem—dalam Islam—adalah bagian dari takdir Tuhan yang harus diubah melalui ikhtiar kolektif, bukan diterima dengan pasrah individual.
Di sinilah MADILOG dan ayat Al-Qur’an justru bertemu, bukan bertentangan. MADILOG menyediakan alat berpikir kritis untuk membaca sistem. Al-Qur’an memberi legitimasi moral bahwa perubahan memang tanggung jawab manusia. Tuhan tidak bekerja secara magis; Dia bekerja melalui hukum-hukum-Nya sendiri.
Religiusitas yang menolak nalar kritis sejatinya sedang menuduh Tuhan tidak konsisten: di satu sisi memerintahkan usaha, di sisi lain mematikan akal. Ini bukan iman, melainkan fatalisme yang dibungkus simbol suci.
Maka, pertentangan MADILOG vs religiusitas hanyalah ilusi. Yang benar-benar berhadap-hadapan adalah iman yang dewasa vs iman yang malas. Iman yang dewasa berani berpikir, bertanya, dan memperbaiki sistem. Iman yang malas berlindung di balik takdir untuk menghindari tanggung jawab sejarah.
Dan barangkali, itulah pesan paling keras dari ayat tadi: Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum—bukan karena Dia tidak mampu, tetapi karena Dia menunggu manusia menggunakan akalnya.